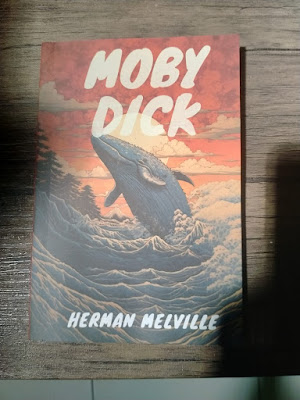“Kafka mah sebenarnya [judulnya] apa aja
lah, tapi saya pilih The Castle,” kata
Eka.
Moby Dick atau Don Quixote, dua judul ini sangat sering saya dengar, tapi belum
kesampaian membacanya. Maka dengan bujet terbatas, meluncurlah saya ke loka
pasar hijau, memindai, dan menukar sejumlah rupiah dengan dua buku versi
ringkas Moby Dick atau Don Quixote. Empat hari berselang,
mereka datang.
“Takdir Moby Dick di negeri ini tampak mirip novel-novel legendaris lain
yang lebih sering disebut daripada dibaca,” tulis Cep Subhan KM dalam
pengantarnya.
Alasannya, kata dia, mungkin karena
novel ini tebal sehingga belum ada terjemahan lengkapnya dalam bahasa
Indonesia. Alasan lanjutannya, pikir saya, barangkali ketebalan itu membuat para
penerbit gentar, takut biaya produksi tak sebanding dengan penjualan.
Setelah menyelesaikan Moby Dick versi ringkas dalam sekali
duduk, saya yakin bahwa novel ini, tentu dalam versi lengkapnya, menyajikan
pertualangan yang dahsyat. Semua material, termasuk plot dan penokohan, juga
lanskap cerita, amat menjanjikan: pertualangan, dendam, ikan paus, laut, para
penombak, darah, badai, dll.
Perhatikan paragraf pembukanya:
“Panggil
aku Ismail. Mengajar adalah profesiku. Tetapi dari waktu ke waktu, aku
merasakan hasrat untuk bertualang. Ketika hasrat itu datang, aku akan
meninggalkan ruang kelas dan pergi ke laut. Ketika aku merasa terjatuh, lautan
terbuka memiliki sesuatu yang dapat mengangkat kembali semangatku.”
Lalu muncul tokoh Queequeg, si
penombak bertato, putra seorang kepala suku yang meninggalkan kampung
halamannya untuk melihat dunia. Sukunya tinggal di sebuah tanah yang jauh
bernama Aotearoa, yang berartinya “awan putih yang panjang”. Ismail menyebut Queequeg
sebagai “raksasa berhati lembut.”
Keduanya bertualang dengan menumpang
Kapal Pequod, kapal penangkap paus yang dipimpin Kapten Ahab yang salah satu
kakinya buntung dimangsa paus putih alias Moby Dick. Dan atas itulah, dendam
kesumatnya menyala sepanjang cerita. Benar-benar bahan cerita yang bagus, bukan?
Para awak kapal lain tak kurang
menarik. Ada Starbuck, seorang pria yang kehilangan ayah dan saudara lelakinya
di laut. Orang kedua bernama Stubb, seseorang yang tidak suka serius. Lalu ada
Flask, dia yang hidup untuk membunuh paus.
Lain itu, ada juga para penombak yang
keberadaannya amat penting di kapal pemburu paus. Mereka orang-orang berani,
sangat kuat, dengan mata yang jernih dan lengan perkasa. Selain Queequeg,
penombak lain bernama Tashtego, seorang Indian Amerika. Dia anggota dari suku
New England yang terkenal kuat. Seorang lagi bernama Daggoo asal Afrika.
Rekan-rekan Daggoo adalah para pejuang pemberani dari sebuah suku di Afrika.
Sementara penombak pilihan Kapten
Ahab adalah seorang pria Arab bernama Fedallah. Dialah si penombak yang bernubuat
bahwa dirinya akan mati duluan dan menuntun sang kapten ke dunia selanjutnya.
“Adalah seutas tali, yang akan
membunuhmu,” kata Fedallah meramal kematian Sang Kapten.
Moby Dick versi lengkap berisi 135 bab plus epilog. Sementara versi pendek hasil meringkas Janet Lorimer ini hanya berisi 10 bab. Saya membayangkan versi pendek ini ibarat kari ayam, atau soto mie, atau rendang, atau ayam bawang, yang semuanya dalam bentuk mie instan. Sedikit terbayang, mencecap secuil, tapi masih jauh dari wujudnya yang hakiki. [irf]