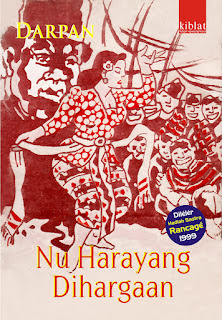 Dalam
pengantar buku kumpulan cerpen ini, Duduh Durahman menyinggung soal komposisi
nama pengarang, yakni Darpan Ariawinangun. Menurutnya, gabungan kedua nama itu
secara kebiasaan bertolak belakang, karena menggabungkan nama yang lumrah
dipakai rakyat jelata dengan nama menak.
Dalam
pengantar buku kumpulan cerpen ini, Duduh Durahman menyinggung soal komposisi
nama pengarang, yakni Darpan Ariawinangun. Menurutnya, gabungan kedua nama itu
secara kebiasaan bertolak belakang, karena menggabungkan nama yang lumrah
dipakai rakyat jelata dengan nama menak.
Nama
Darpan, tambahnya, sederajat dengan nama Salhiam, Mang Uham, atau Kang Nurhayi.
Sementara Ariawinangun betul-betul nama ningrat. Lain itu, kata Duduh,
pengarang kiwari jarang yang memakai nama yang berbau priyayi.
Namun
di sejumlah bukunya, pengarang hanya menyantumkan Darpan—nama merakyat itu—tanpa
menambahkan nama belakang. Saat menamatkan 15 cerpen dalam buku ini, kiranya
tepat jika dia hanya memakai nama Darpan, karena seluruh cerita yang ia reka
menggambarkan kehidupan rakyat jelata dengan segala kemalangan dan kepahitannya
dalam melakoni hidup.
Darpan
lahir pada 4 Mei 1970 di Sungai Ula, Cibuaya, pesisir Karawang. Berbeda dengan
sejumlah pengarang Sunda yang lebih senior darinya, yang kebanyakan berasal
dari wilayah Priangan, Darpan orang utara. Bahasa Sunda yang ia pakai pun
terdapat beberapa perbedaan dengan dialek Priangan. Meski demikian, di bagian
akhir buku ini terdapat keterangan “Bahasa Wewengkon”, yakni kosakata yang
dipakai Darpan dan mungkin tidak biasa atau jarang didengar orang orang Sunda
dari wewengkon/wilayah lain di Jawa Barat.
Sebagai
orang pesisir, tak heran jika beberapa cerpennya mempunyai latar kehidupan
nelayan dan petambak. Laut, pantai, dan muara menjadi tempat sehari-hari
sejumlah tokohnya, bukan sekadar tempat rekreasi seperti misalnya dalam novel Rajapati
di Pananjung (1985) karangan Ahmad Bakri.
Rajapati,
Isu Lingkungan, dan Politik
Pada
2010, seorang kawan menulis cerpen yang dimuat di majalah Manglé. Ia
menyudahi kisahnya dengan rajapati atau pembunuhan. Menurutnya, pilihan itu
diambil karena ia ingin akhir yang fantastis.
Sejauh
pembacaan saya terhadap cerpen-cerpen Sunda, rajapati memang beberapa kali
muncul di penghujung kisah. Polanya sama, pengarang mula-mula membangun konflik
yang eskalasinya kian menanjak, lalu menempatkan tragedi pembunuhan di bagian
akhir yang dimaksudkan sebagai klimaks. Awalnya mungkin pembaca tak akan
mengira demikian, tapi jika lama-kelamaan akan terbiasa dan mampu
memprediksinya.
Cerpen-cerpen
Darpan pun tak lepas dari rajapati. Motifnya rupa-rupa. Berseteru dengan anak
sendiri gara-gara berbeda pendapat dalam merespons permasalahan sosial yang
timbul akibat korupsi perangkat desa dalam cerpen “Taleus Ateul”. Protes dan
frustasi akibat proyek pembangunan menggusur kampung dalam cerpen “Peuting nu
Hareudang”. Dan cemburu karena istri ditiduri tetangga dalam “Si Ato Miara
Jago”.
Selain
dalam “Peuting nu Hareudang” yang menceritakan hilangnya sebuah kampung karena
pembangunan pabrik, isu lingkungan dan ekonomi juga muncul dalam cerpen “Layung
Geus Ririakan”—orang tua yang pendengarannya sudah buruk yang kehilangan sawah
karena dijual oleh anaknya kepada orang-orang kaya, dan “Helikopter”—para petambak
penghasilannya mulai berkang akibat pencemaran air.
Sedangkan
isu politik selain muncul dalam cerpen “Teleus Ateul”, juga hadir dalam “Cikopi
Sagelas”—rakyat jelata yang terhindar dari tekanan/sandra politik aparat desa
karena anaknya berbeda pilihan dalam pemilihan lurah. Di pengujung kisah, Mang
Karma, rakyat kecil itu akhirnya bisa kembali merasakan kehidupan yang tenang
tanpa paksaan dan kesenangan semu yang sempat diberikan pemerintah desa.
“Nya
ieu dunya aing. Dunya sagelas cikopi isuk-isuk, bari bébas mikir pigawéeun poé
ieu. Henteu dipapaksa ku batur, henteu kudu sieun ku batur. Ah, naha aing
salila ieu kaparabunan ku nu teu puguh? Ninggalkeun dunya aing nu sakieu bébas
merdékana? Kétang aya hikmahna, aing jadi nyaho talajak hiji-hijina jelema. Mangsabodo,
saha nu rék jadi lurah minggu hareup,” kata Mang Karma.
Cerpen
lain yang juga memakai tema politik adalah “Nu Luas Ninggalkeun” dan “Patung
jeung Hayam”. Meski cerpen “Nu Harayang Dihargaan” memang cukup menonjol
sehingga dipilih jadi judul buku ini, yang menurut Duduh Durahman dalam
pengantarnya mempunyai kesan “ngagalura, keras jeung kasar, unsur dramatikna
kuat... carpon anu pangneundeutna, tapi pepel,” tapi menurut saya pribadi “Patung
jeung Hayam” adalah cerpen yang gaya penceritaannya paling unik.
Dalam
“Patung jeung Hayam” Darpan begitu tapis menggugat arti kepahlawanan yang pada
umumnya hanya berhenti pada simbol. Diceritakan bagaimana pembangunan sebuah
patung pahlawan memakan banyak biaya sehingga melebihi dari anggaran
semestinya. Akibatnya, warga sekitar patung “katempunan”. Harta benda mereka
yang tak seberapa dipakai untuk mendukung pembangunan patung tersebut. Bahkan seekor
ayam warga pun akhirnya dirampas.
Lain
itu, para pejabat dari kota yang melakukan perjalanan dinas ke desa untuk mengontrol
dan memeriksa pembangunan patung kerap minta dilayani dengan berlebihan, salah
satunya minta “ayam”.
Kumpulan
15 cerpen ini seluruhnya memotret nasib rakyat kecil yang hidupnya tak putus
dirundung malang. Suara Darpan adalah suara wong cilik pesisir utara Jawa
Barat dengan segala persoalannya. [irf]
No comments:
Post a Comment