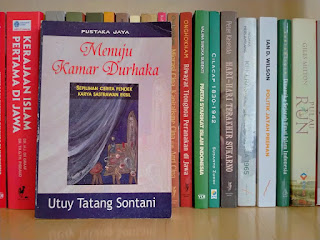Catatan Perang Korea (Mochtar Lubis)
Mochtar Lubis berangkat ke Korea Selatan saat Perang Korea telah berjalan sekitar tiga bulan. Seoul telah hancur dan pasukan Korea Utara telah mundur. Meski Perang Korea berlangsung selama tiga tahun, tetapi catatan Mochtar Lubis terkesan bahwa perang akan segera berakhir. Dia hanya sekali terperangkap dalam kontak tembak ketika patroli ke Ujingbu, itu pun hanya sebentar.
Menurutnya, wartawan yg meliput perang ini bersamanya
hanya sekitar 30 orang. Kebanyakan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Di luar itu masing-masing hanya satu dari Filipina, Indonesia, dan Turki.
"Kebanyakan wartawan asing yg datang ke
Korea [...] datang untuk membuat laporan-laporan 'ar-exploits'
(kegagahan-kegagahan dan pengalaman-pengalaman perang) serdadu-serdadu AS.
Mereka tidak atau jarang sekali berhubungan dengan rakyat," tulisnya.
Lain itu, imbuh Mochtar, para wartawan juga
hanya memberitakan para serdadu yg berasal dari daerahnya masing-masing.
Seorang wartawan dari Texas utara misalnya, ia hanya mewartakan para serdadu yg
berasal daerah tsb.
"Dari hari pertama saya turun di Pusan,
saya berjanji pada diri saya sendiri untuk mencari hati bangsa Korea ini,"
tulis Mochtar.
Mungkin inilah yg mendorong Mochtar Lubis
mengabaikan "kegagahan" perang dan mengisahkan para korban serta
kampung-kampung yg berbau busuk dari pupuk kotoran manusia, juga kota yg bau
amis darah. Sayangnya, ia menulis secara selewatan.
Rumah Kertas (Carlos Maria Dominguez)
Bluma Lennon namanya. Dosen di Universitas Cambridge ini tewas tertabrak mobil saat berjalan sambil membaca buku Emily Dickinson.
"Buku mengubah takdir hidup orang-orang," tulis si pengarang.
Tak lama setelah itu, sebuah buku tiba di meja
mendiang Bluma dari seorang bibliofil di Uruguay bernama Carlos Brauer. Orang
ini hidupnya dipenuhi buku. Seluruh ruangan rumahnya sesak. Mobilnya ia berikan
ke kawannya agar garasi bisa dipenuhi buku. Ia siang malam membaca buku sampai
akhirnya indeks buku yg tengah ia buat terbakar.
Brauer kemudian memboyong buku-bukunya ke sebuah
daerah terpencil di tepi laut dan membuat pondok yg dibangun dari buku-buku
itu, termasuk lantai dan dindingnya. Buku hanya membawanya pada kesia-siaan.
Juga ini:
"Seorang perempuan tua pergi menemuinya dan
meminta dia menangkal guna-guna yg membuat perutnya menggembung besar sampai
seperti mau meletus. Perempuan itu pulang dengan kecewa, menyebut bahwa orang
itu dukun sihir yg tak punya kekuatan apa-apa."
Brauer serupa segelintir orang di Buenos Aires
yg kata Dominguez: halusinatif. Begini tulisnya, "Orang-orang jadi kaya
raya dalam semalam berkat buku-buku yg payah, yg dipromosikan habis-habisan
oleh penerbitnya, di suplemen-suplemen koran, melalui pemasaran, anugerah-anugerah
sastra, film-film acakadut, dan kaca pajang toko-toko buku yg perlu dibayar
demi ruang untuk tampil menonjol."
Seperti manusia, buku punya nirfaedahnya
masing-masing.
Serupa manusia, buku banyak yg tidak berguna.
Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang (Luis Sepulveda)
Zorbas, kucing di pelabuhan Hamburg yg gendut dan berbulu hitam. Sekali waktu seekor camar jatuh di dekatnya. Tubuh camar itu berlumur minyak hitam dan bau, dan itulah penerbangannya yg terakhir. Sebelum ajal merenggutnya, camar itu bertelur dan meminta Zorbas berjanji untuk merawat dan mengajari anaknya terbang, kelak.
Sejumlah kucing pelabuhan kemudian menguburkan
camar malang itu pada suatu malam yg diliputi duka:
"Dan sekarang kita ucapkan selamat tinggal
kepada camar ini, korban bencana yg disebabkan oleh manusia. Mari julurkan
leher ke arah bulan dan meongkan lagu perpisahan kucing-kucing pelabuhan."
Kemudian kucing-kucing pelabuhan itu mengerjakan
apa yg mesti mereka lakukan: menepati janji Zorbas.
Satu lagi isu lingkungan dari Luis Sepulveda.
Marjin Kiri menamai seri ini sebagai Pustaka Mekar, seri bacaan untuk anak-anak
dan remaja. Cocok untuk warganet yg doyan mengeong, "anaknya mulai aktif
ya, Bun."
Gadis Minimarket (Sayaka Murata)
"Aku belum punya pengalaman seksual dan aku tak punya kesadaran soal seksualitasku. Aku hanya tak peduli dan tak pernah merisaukannya. Tapi, mereka membicarakan semua itu dengan asumsi aku menderita," ujar Furukura.
Gadis ini berusia 36. Ia sudah 18 tahun kerja di
minimarket sebagai karyawan tidak tetap, belum pernah pacaran, dan direcoki
dunia di sekelilingnya, kecuali benda-benda mati di minimarket.
Sejak kecil ia dianggap berbeda dengan anak
kebanyakan, aneh, bahkan mengerikan. Padahal, ia hanya kritis, tetapi dinilai tak
lazim. Untuk dianggap sama dengan orang lain, ia akhirnya menjadi pendiam.
Bekerja di minimarket adalah caranya agar terlihat normal.
"Bekerja di minimarket kerap disepelekan.
Buatku itu menarik, dan kalau ada yg melakukan itu padaku, aku suka menatap
wajahnya. Dan setiap kali melakukan itu aku merasa: seperti itulah
manusia."
Mulanya, dia pikir, di lingkungan pekerjaannya,
orang-orang tak akan rewel bertanya soal jodoh, tapi rupanya sama saja.
"Rasanya sekarang dia menurunkan levelku
dari pegawai minimarket menjadi betina dari spesies manusia," ungkapnya
setelah sang manajer mulai banyak tanya.
Kisah yg menerbitkan simpati, juga kejengkelan.
Relasi manusia yg diukur dengan norma-norma mayoritas, menyeret si sedikit ke
jurang keasingan, lebih tepatnya diasingkan. Sayaka Murata, lewat gadis 36
tahun ini, seperti ingin menonjok arogansi itu.
Aib dan Nasib (Minanto)
Kisah-kisah yg mirip di koran Lampu Merah, dijahit, diceritakan ulang dalam bentuk penulisan "fragmen-fragmen episodik dengan alur maju mundur." Kira-kira demikian keseluruhan karya Minanto ini.
Aib dan Nasib yg menjadi pemenang 1 Sayembara
Novel Dewan Kesenian Jakarta 2019, sepenuhnya berisi konflik. Hari-hari
dibangun dari perkelahian, pemerkosaan, tengkar bapak-anak, taruhan bersenggama,
pencurian, kekerasan rumah tangga, hingga laku politikus busuk yg menagih
kembali "serangan fajar" karena dia tak terpilih.
Dalam kondisi sosial masyarakat yg demikian,
masih punya tempatkah sang "aib"? Apalagi yg mesti disembunyikan,
ditutupi, atau sesuatu yg bikin malu dari ikatan-ikatan sosial yg hampir
seluruhnya berisi kekerasan, di tubir dalam jerat kekinian berupa pemilu dan
medsos?
Ngilu rasanya menamatkan novel ini. Membaca 263
halaman berita-berita kriminal dan kemiskinan yg tumpang tindih dan
bertubi-tubi. Dan seperti juga tertulis dalam sampul belakang, Minanto intinya
hanya menyodorkan satu pertanyaan:
"Malah aku heran, kenapa TV-TV tidak datang
ke Tegalurung buat siaran berita. Padahal kukira setiap hari pastilah ada
berita kriminal, apalagi di Tegalurung. Tidak pagi tidak siang tidak sore tidak
malam."
Tempat Terbaik di Dunia (Roanne van Voorst)
Seorang antropolog asal Belanda membagikan pengalaman hidupnya selama setahun di sebuah permukiman kumuh di bantaran sungai di Jakarta yg akhirnya digusur pemerintah. Ia menuliskannya dalam tujuh bagian. Isinya--karena mudah saya bayangkan, juga beberapa kali mengalaminya--jadi terkesan klise.
Roanne, begitu ia biasa dipanggil, berkisah
tentang kepemilikan portofon (walkie talkie) untuk mendapat informasi dari
penjaga pintu air, jaringan listrik yg buruk dan berbahaya, budaya korupsi dan
amtenar brengsek, akses kesehatan yg tak terjangkau, persepsi seks, aktifitas
ekonomi semenjana, dan budaya komunal yg mencekik privasinya.
Meski cukup lama (setahun dan masih bolak-balik
setelah kampung itu digusur), tapi dari paparannya, saya menangkap bias.
Dirinya yg seorang bule, saya kira, di mata warga yg ia teliti--stereotip
padanya tidak sepenuhnya tanggal. Sebaliknya, Roanne juga banyak pukul rata,
atau katakanlah stereotipnya terhadap orang Indonesia cukup pekat. Ia misalnya
menulis, "Budaya Indonesia adalah budaya 'kami', budaya 'kelompok' dan
dalam 'kelompok'."
Ihwal hidup komunal yg ia jalani selama hampir
setahun di tempat penelitiannya, membuatnya menyempatkan diri pergi sendirian.
Baginya, menjadi anonim tanpa ada yg menyapa dan menghabiskan waktu sendirian
adalah kebutuhan untuk memulihkan energi. Celakanya, saat ia duduk di bangku
bioskop hendak menikmati kesendirian, tiba-tiba seorang ibu dan tiga orang anak
merecokinya. Saya kira, tak perlu jadi orang Belanda untuk merasakan
kejengkelan yg sama dengannya.
Hari-hari Terakhir Sukarno (Peter Kasenda)
Bermula dari dua kekuatan yg berhadap-hadapan, PKI vs Angkatan Darat, Sukarno akhirnya tak mampu lagi menjadi penyeimbang. AD menunggu dalih, PKI masuk perangkap, maka terjadilah pembantaian besar-besaran.
Pagi 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih
kendali AD, ia tak mengizinkan Pangdam Jaya (Umar Wirahadikusumah) menghadap
Sukarno. Lalu berturut-turut gelombang demonstrasi, penyusupan pasukan liar,
hingga Supersemar. Kekuasaan Sukarno perlahan digerogoti hingga Nawaksara
ditolak MPRS. Lalu mandat dicabut, penahanan Istana Bogor, Batutulis, dan Wisma
Yaso.
Ngilu mengikuti persalinan kedua Indonesia ini.
Bagaimana sebuah orde dipreteli perlahan, kerawanan perang saudara, dan episode
kesepian seorang orator yg dijauhkan dari keriuhan.
Catatan medis beberapa perawat tentang Sukarno,
meski kurang lengkap, tapi cukup menggambarkan penderitaan hari demi hari sang
proklamator yg kian lemah.
Dua hari sebelum wafat, Bung Hatta datang
menengoknya di RSPAD.
"Hatta, kau di sini...?"
"Ya, bagaimana keadaanmu, No?"
Tangan Hatta memegang tangan kawannya itu.
Sukarno pun terisak seperti anak kecil.
"No..."
Hatta tak melanjutkan kata-katanya. Bibirnya
bergetar menahan kesedihan. Bahunya terguncang-guncang. [irf]