Judul Buku : Natsir, Politik Santun di antara Dua Rezim
Penulis : Tim Liputan Khusus TEMPO
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Cetakan Pertama : Januari 2011
Tebal : xi + 163 hlm
Itp, 2 Des ‘ 11
Penulis : Tim Liputan Khusus TEMPO
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Cetakan Pertama : Januari 2011
Tebal : xi + 163 hlm
“Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka soal itu lagi.”
“Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula?. Nanti saja.”
***
Kira-kira di pertengahan tahun 2003, waktu darah masih disesaki
idealisme mahasiswa, saya sempat berbincang cukup lama dengan seorang
kawan yang kampung halamannya di Sumatera Barat. Dan perbincangan
sampailah ke soal pemimpin. Barangkali karena masih mahasiswa, dan
entah kenapa, waktu itu kondisinya cukup bersemangat untuk mengkritik
para pemimpin; dari Presiden sampai Direktur Politeknik. Semuanya tak
habis dijadikan bahan perbincangan sambil sibuk mencari
keburukan-keburukannya. Mahasiswa seperti dikutuk untuk seolah-olah
kritis, jejak berliku sejarah pemuda dan mahasiswa tak habis
dijejal-jejal di batok kepala, lalu dikenang sebagai sebuah romantisme
masa muda ketika semuanya disembelih oleh waktu yang bergegas,
tersuruk-suruk meluncur ke dunia kerja yang seumpama secangkir kopi;
wangi, nikmat, kadang melenakan, juga sekaligus pahit.
Beberapa kalimat meluncur dari mulut saya, “Bung ini kan asli
Sumatera Barat, orang Minang, apakah Bung tidak merasa defisit pemimpin
dan teladan yang dulu bederet-deret dari daerah Bung?.” Dia tak
menjawab.
Saya meneruskan, “Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Natsir,
sampai Buya Hamka, semuanya berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah,
sekarang siapa yang tersisa?, siapa yang menggantikannya?, tidak ada!.”
Dia, kawan saya itu, tetap saja diam tak bersuara, hanya asap
cigarettenya saja yang meluncur dari mulut lalu rerak berhamburan.
Barangkali dia setuju dengan ucapan saya.
Sepenggal ingatan tentang perbincangan itu berhasil menggarami saya
untuk menulis sekedarnya, untuk mengulas buku Natsir. Barangkali bukan
sebuah resensi, tapi beginilah jadinya :
***
Dialog antara Natsir dan Soekarno yang saya tulis di awal catatan
ini adalah awal dari hubungan yang mulai mesra antara kedua tokoh
tersebut setelah sebelumnya sempat terlibat polemik tajam di surat
kabar. Mereka berseberangan pendapat ihwal kiprah dan akibat yang
ditimbulkan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menjadi aktor runtuhnya
Turki Ottoman. Seperti yang ditulis tim TEMPO, “Soekarno menganjurkan
faham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideology seraya memuji
‘sekularisasi’ yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan
Natsir menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan
akibat-akibat negatifnya. Tulisan-tulisan Natsir jernih dan
argumentatif.”
Natsir tidak memilih menyeret-nyeret adu argument di wilayah abstrak
dengan membawanya ke wilayah konkrit, ya persoalan telah menunggu di
depan; Belanda masih punya keleluasaan untuk mengobrak-abrik Indonesia.
Maka Natsir pun kemudian mengemban tugas sebagai Menteri Penerangan
sebanyak tiga kali dalam tiga Kabinet Sutan Sjahrir, berturut-turut
pada 3 Januari 1946 sampai 27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban
dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29 Januari 1948 hingga 19 Desember
1948. “Hij is de man (dialah orangnya)”, begitu kata Soekarno waktu
Sjahrir mengusulkan Natsir untuk menjadi Menteri Penerangan. Soekarno
tidak keberatan sama sekali. Pengalamannya berpolemik dengan Natsir
membuat Soekarno percaya bahwa Natsir adalah seorang yang piawai dalam
menyusun kata-kata. Demikianlah sejarah mencatat, bahwa perseteruan
tidak selamanya berpangkal pada mencerca kelemahan, tapi sebaliknya
justru mengangkat kelebihan-kelebihan lawan polemik untuk dimanfaatkan
pada medan yang lebih nyata dan lebih luas. Dan Natsir pun kemudian
berkarya untuk bangsa di masa pemerintahan yang pertama.
Ketika kekuasaan Soekarno tenggelam dan digantikan oleh Soeharto,
Natsir masih dalam jeruji penjara karena terlibat dalam PRRI. Suatu
hari datanglah orang suruhan Soeharto untuk membicarakan tentang usaha
pemerintah untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia yang hancur akibat
operasi “Ganyang Malaysia” yang dilancarkan Soekarno. Waktu itu
komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur beku.
Awalnya Soeharto sempat mengirim dua orang kepercayaannya, yaitu Ali
Moertopo dan Benny Moerdani, tapi misi keduanya gagal, Malaysia seolah
menghindar. Maka Natsir pun menjadi harapan karena ia dikenal dekat
dengan Tengku Abdul Rahman. Natsir hanya menulis surat pendek : “Ini ada
niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara
Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.” Tak lama
kemudian surat itu dibawa ke Kuala Lumpur dan sampai ke tangan Tengku
Abdul Rahman. Segera setelah menerima surat dari Natsir, ia berkata,
“Datanglah mereka besok ke tempat saya.” Esok harinya Delegasi Indonesia
diterima. Dan hubungan kedua negara pun berangsur cair.
***
TEMPO sebagai majalah berita mingguan memang rajin menulis masalalu
(sejarah), meskipun sehari-harinya bergelut dengan masakini (news).
Maka para wartawan TEMPO adalah mereka yang bekerja “depan-belakang”;
melaju kencang menulis berita-berita terbaru, tapi juga kadang-kadang
bertamasya dengan menulis sejarah yang bececeran di belakang. Dan inilah
salahsatu buku sejarah yang ditulis dengan pendekatan jurnalistik.
Aroma suram, kaku, dan membosankan yang biasanya memancar dari buku-buku
sejarah, di tangan para waratawan ini berubah menjadi memesona dan
penuh dramatik. Barangkali itulah sebabnya Arif Zulkifli menulis
pengantar di buku Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman : “Dalam
pendekatan jurnalistik, yang diharapkan muncul adalah pesona
sejarah---meski tidak berarti fakta disajikan serampangan dan tanpa
verifikasi. Tujuan jurnalisme adalah mengetengahkan fakta dengan
menarik, dramatik tanpa mengabaikan presisi.”
Dan sejarah, apa sesungguhnya yang kita harapkan dari sejarah?.
Perbincangan kini tengah ramai di dunia maya, bahwa Indonesia dijajah
selama 350 tahun alias tiga setengah abad, angka itu sesungguhnya
adalah tiga setengah abad bangsa-bangsa asing kesulitan menaklukkan
kepulauan Nusantara yang senantiasa ditaburi bibit perlawanan sengit
anak-anak pribumi. Di titik ini sejarah barangkali adalah batu tapal
doktrin yang membuat bangsa ini inferior berkepanjangan. Bagaimana
tidak, anak belia yang baru saja menginjakkan kakinya di kelas pertama
sekolah dasar, tiba-tiba langsung dihantam palu godam oleh bapak dan
ibu gurunya, bahwa bangsanya adalah bangsa pecundang. 350 tahun dijajah
adalah “kebenaran” yang terus dijejalkan setiap kali anak-anak itu
bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Perlahan mentalnya menyusut. Tak
terbayang lamanya dijajah selama tiga setengah abad : pecundang di
atas pecundang !!.
Hal itu pun masih belum cukup, karena sejarah seringkali
disimpangkan. Para penguasa rajin sekali membuat distorsi. Kebenaran
menjadi kalang kabut. Naskah-naskah yang diterbitkan menjadi buku
banyak yang terpojok di sudut-sudut ruangan dingan dan berdebu. Ya,
sejarah memang masalalu, sedangkan hidup tidak pernah berjalan mundur,
juga tidak mengendap, hidup terus saja menelan detik demi detik yang
berparade di titian sisa hidup. Maka membaca sejarah adalah sesuatu
yang seringkali dianggap hanya membuang waktu. Maka dari itu, dengan
digawangi para awak redaksi yang lincah menulis diksi, TEMPO berusaha
menghadirkan “hal yang basi” dengan mengemasnya secara seksi tanpa abai
presisi.
Buku Natsir ini, walaupun hanya sebuah biografi mini, tapi terasa
menyesap ke urat nadi. Tidak terlampau tebal, malah hanya di bawah 200
halaman, tapi berhasil memaparkan perjalanan Natsir dalam taman luas
sejarah Indonesia. Dari masa kecil Natsir, masa sekolah, bergaul dengan
A. Hasan (ulama pendiri Persis di Bandung), masa-masa berkecimpung
dalam pemerintahan Soekarno, terlibat dalam gerakan PRRI, tetap kritis
di masa pemerintahan Soeharto, sampai pergerakannya di lapangan dakwah.
Semuanya disajikan dengan racikan yang “menggoda”. Judul-judul dalam
setiap tulisan pun terasa begitu bernuansa prosa. Ini memang bukan buku
sastra, tapi daya pemantiknya tak kalah dengan cerita-cerita fiksi.
Dan waktu benar-benar telah menjadi ragi yang baik untuk
memfermentasikan perjalanan hidup anak manusia. Di tengah kehidupan
berbangsa yang miskin teladan, kumpulan catatan perjalanan hidup Natsir
ini berhasil mengembangkan sebuah kerinduan. Rindu pada sosok seperti
Natsir. Di sampul belakang buku ini tertulis :
“Mohammad Natsir orang yang puritan. Tapi kadangkala orang yang
lurus bukan berarti tak menarik. Hidupnya tak berwarna-warni seperti
cerita tonil, tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata
dan perbuatan ini punya daya tarik tersendiri. Dalam hidupnya yang
cukup panjang, di balik kelemahlembutannya, ada kegigihan seorang yang
mempertahankan sikap. Ada keteladanan yang sampai sekarang membuat kita
sadar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten, dan
bersahaja itu bukan mustahil meskipun penuh tantangan. Hari-hari
belakangan ini kita merasa teladan hidup seperti itu begitu jauh,
bahkan sangat jauh.” [ ]
Itp, 2 Des ‘ 11
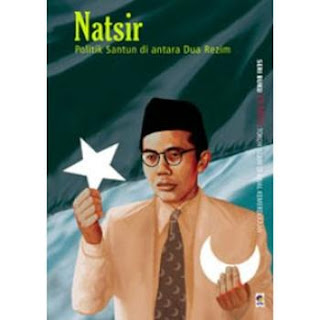
No comments:
Post a Comment